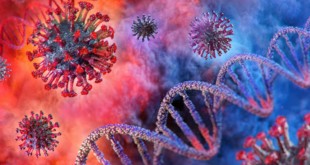dakwatuna.com – Kisah ini mungkin tak sepadan hikmahnya dibanding Menikmati Shalat di Bawah Guyuran Hujan ataukah Monolog Terhadap Diri (maaf kalau menyebutkan judul), dua judul kisah yang pernah penulis baca di sebuah majalah Islam: Tarbawi. Namun rasanya indah jika aku berbagi melalui goresan ini. Hari bisa saja terlupakan olehku tetapi momen tak akan pernah lekang dalam ingatan ini. Tiga tahun lamanya kami sekeluarga baru bisa mempunyai kesempatan sejam untuk bertemu dengan kakak. Dan tiga tahun yang lalu pula kami dikumpulkan oleh-Nya dalam sebuah kisah yang tak pernah kami bayangkan, adikku dipanggil menghadap-Nya secara tiba-tiba dalam sebuah kecelakaan. Kami memang hidup terpisah, ibu dan ayah mencari nafkah di Papua. Kakak bertugas di Jayapura, tepatnya Agats, Merauke, dua adikku tinggal bersama nenek, dan saya sendiri menjalani kuliah di Kota Anging Mammiri. Itu terakhir kali kami berkumpul. Saat adikku tak bisa lagi berkata apa-apa.
Waktu yang lumayan lama itu serasa terobati ketika kakak menghubungiku bahwa dia akan berangkat ke Bogor dalam rangka dinas dan kemungkinan besar pesawat yang ditumpanginya transit selama sejam di Makassar. Segera kuhubungi orang tua di kampung dan mengabarkan tentang berita bahagia itu. Namun, jauh dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku merasa sangat sedih karena waktu itu tidak akan pernah terwujud bagiku. Ada agenda yang tak bias aku cancel karena ini agenda nomor satu bagiku. Kalau para pembaca yang budiman aktif dalam sebuah pengajian, tentu akan mudah menebak agenda nomor satu itu adalah tarbiyah. Sedih rasanya memikirkan hal itu. Namun karena tak ingin mengecewakan kakak, aku pun mengiyakan untuk menemuinya di Bandara tepat pukul 16.00 WITA. Sudah kumantapkan niat melangkah ke majelis ilmu, jadi apapun yang akan terjadi kuserahkan semuanya pada yang Kuasa. Tak terasa waktu pertemuan kami dalam majelis pun usai. Suara adzan Maghrib sebentar lagi berkumandang. Segera pamit tanpa memperpanjang rasa penasaranku tentang materi yang dibawakan dalam pengajian tadi. Terus terang, batinku tidaklah tenang. Dari dalam muncul rasa ingin menyalahkan keadaan, tetapi aku tetap optimis bisa bertemu dengan kakak. Tanpa pikir panjang lagi, kendaraan roda dua melaju dengan kencangnya, tiba-tiba ‘ding–dong’ ponselku berbunyi, pertanda ada pesan. ‘Jam 7 saya sudah harus melapor, kamu sudah di mana?’
Motor melaju dengan cepat. Suara adzan pun mulai berkumandang. Sudah masuk waktu Maghrib. Hampir sepuluh masjid yang kulewati, sesekali ada niat untuk shalat dahulu baru melanjutkan. Tetapi, tentulah aku tak bisa bertemu kakak. Air mata ini bagai deras hujan disertai gemuruh. Sakit, sedih, dan pilu, itu yang terasa. Berusaha menenangkan diri dengan berdzikir dan istighfar. Akhirnya tinggal menghitung beberapa menit, aku tiba di bandara. Cemas terus saja memburu. Cemas dan was-was kerap muncul bila kewajiban pada yang Kuasa belum terlaksana. Nah, itulah aku. Berada pada posisi belum menunaikan kewajiban.
Tunggu aku, Kak! Pintaku melalui sms, meski kutahu sudah sangat terlambat. Teriring tangis, sedih, was-was. Tangis karena sedih yang berlebihan dan was-was karena shalat belum kutunaikan. Kutegarkan diriku bahwa ini adalah takdir-Nya. Ikhtiar dan doa sudah kulakukan, namun jika Dia berkata lain untuk pertemuan yang dinanti ini, maka tawakal jalan yang terbaik.
Tepat gerbang jalan masuk bandara Sultan Hasanuddin yang kulalui. Sepintas kulihat motor matic dikendarai seorang bapak bersama istrinya, juga anaknya di bagian depan. Anak kecil itu melambaikan tangan dan berteriak memanggil namaku, pas terhenti di lampu merah. Semakin hancur rasanya, itu pertanda bahwa kesempatan bertemu dengan kakakku pupus sudah. Motor yang dikendarai sekeluarga tadi tidak lain adalah ayah, ibu, juga adikku. Tak masalah tak bertemu dengan kakak, masih ada ayah dan ibu juga adik, cukup lama juga tak bertemu dengan mereka yang kusayangi. Kuputar balik motorku menuju lampu merah tadi dengan harapan mereka pasti menungguku. Dua kali kulalui lampu merah itu, namun jejak mereka tak ada. Pasti sudah pulang. Satu-satunya yang terpikir adalah mereka sangat tega. Komplit sudah kesedihanku, kulanjutkan langkah masuk ke bandara.
Apa ini teguran dari Allah karena saya belum juga shalat Maghrib, sementara waktu Isya tinggal menghitung detik. Terlanjur basah, mandi saja. Maghrib dan Isya nampaknya harus saya kerjakan pada waktu Isya (jamak). Istighfar tiada henti kulantunkan, aku yakin ini adalah peringatan untukku bahwa segala sesuatu harus niatkan Allah dahulu barulah yang lain. Sebaiknya shalat di rumah atau tidak, pikiranku masih mendua. Di rumah saja, supaya langsung tidur setelahnya. Namun, panggilan untuk shalat di masjid itu lebih kuat. Akhirnya, di antara sedih dan was-was yang hampir membuatku menangis sepanjang perjalanan, kuputuskan untuk menenangkan pikiran dengan berusaha shalat khusyuk di masjid bandara. Batin sakit. Raga lelah. Namun, di tengah remangnya lampu masjid, shalatku terasa nikmat. Batinku berbisik pelan, ternyata shalat dalam susah itu sangat nikmat. Air mata deras bercucuran. Istighfar terucap sekian kali. Bila susah dihadirkan agar manusia merasakan nikmatnya shalat, maka sungguh aku ingin merasakannya kembali. Wallohu’alam bissawab.
Redaktur: Lurita Putri Permatasari
Beri Nilai: dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat