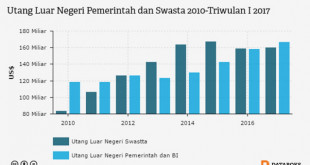dakwatuna.com – Imam Syafi’i dalam salah satu bait syairnya mengungkapkan kalimat yang indah dan penuh makna: “Tidak ada kesulitan yang terus-menerus terjadi pada diri seseorang tanpa adanya kesenangan. Begitu pula tidak ada kesenangan terus-menerus tanpa adanya kesulitan.” Kesulitan dan kesenangan selalu datang silih berganti seperti perputaran siang dan malam. Manusia akan merasa bosan, jika mentari terus bersinar. Manusia membutuhkan rembulan, agar istirahat malamnya menjadi sempurna dan menyegarkan.
Pergantian itu menjadi bagian dari sunnatullah kehidupan, seperti dalam surat Ali Imran: 140 yang berbunyi: “Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka Sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.”
Bagaimana Allah memberikan penilaian terhadap perjalanan hidup manusia? Dua keadaan itu (kesulitan dan kesenangan) tidak jadi masalah, keduanya tidak dijadikan tolok ukur keberhasilan seseorang. Bukan kesulitan dan kesenangan yang dinilai, karena keduanya adalah sunnatullah yang akan terjadi pada manusia. Keduanya mesti ada, agar kehidupan ini bisa berjalan normal. Orang yang sedang dalam kesulitan dan orang yang sedang dalam kesenangan adalah peran yang keduanya harus ada dalam kehidupan. Kedua keadaan itu pada diri seseorang bisa menjadi jalan seseorang menggapai yang tertinggi di sisi Allah.
Seseorang dengan kesulitannya dapat menggapai surga Allah swt. Begitu pula, seseorang dengan kekayaannya juga memperoleh peluang untuk meraih surga. Bisa dibayangkan kalau kesenangan adalah ukuran masuk surga, maka hanya konglomerat, jutawan, orang-orang kayalah yang mampu meraihnya. Sebaliknya, bisa dibayangkan kalau hanya kesulitan yang membawa seseorang ke surga, maka hanya orang yang menderita, terkena banyak musibah yang mampu menggapainya. Di sinilah letak kemahaadilan Allah swt, seperti yang digambarkan dalam surat at-Tin: 8 yang berbunyi:
“Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?”
Benar-benar terbukti, tidak ada yang maha adil memberi nilai selain Allah. Tidak ada yang lebih objektif dalam memberikan penilaian. Berbeda dengan manusia, yang penilaiannya selalu bias. Penilaian mansuia selalu mengandalkan dan mengandaikan tolok ukur yang sama. Padahal jika diperhatikan semua manusia memiliki kondisi awal yang berbeda. Bagaimana mungkin penilaian menjadi objektif dan akurat jika objek yang dinilai sudah memiliki nilai dasar atau modal nilai yang berbeda?
Namun demikian, bukan berarti semua menjadi nisbi atau relatif. Dengan segala kesadaran ini, maka manusia harus lebih berhati-hati, lebih bertanggungjawab dan bersunggug-sungguh dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu. Manusia tidak gegabah, sembrono, dan terburu-buru dalam memberikan penilaian. Penilain harus dilakukan dengan gambaran sekomprehensif mungkin. Kesungguhan itu akan mendekatkan penilaian semi objektif manusia dengan penilian objektif Allah. Wallahu a’lam
Redaktur: Deasy Lyna Tsuraya
Beri Nilai: dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat